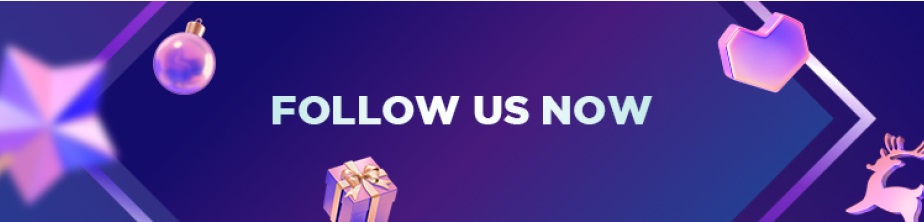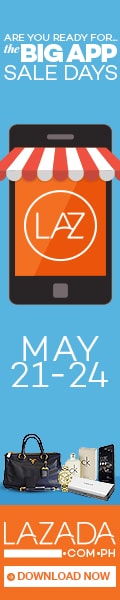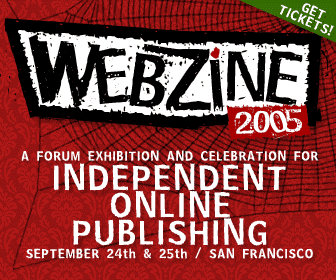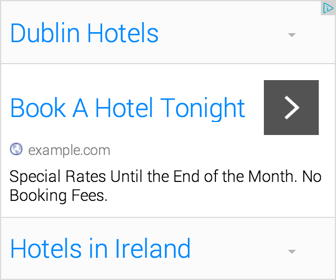Penulis : Lilis Suryani, Euis Sukarsih, Nia Kurniasih
Kekerasan seksual yang dialami anak oleh orang-orang terdekat mereka bukan sekadar bencana pribadi, tetapi juga merupakan masalah sistemik yang menunjukkan kekurangan dalam struktur sosial dan pola asuh. Insiden yang terjadi di Kabupaten Garut pada April 2025, di mana seorang gadis berusia lima tahun menjadi korban kekerasan seksual berkali-kali oleh ayah dan pamannya, mengungkapkan kenyataan kelam bahwa rumah—yang seharusnya menjadi ruang teraman bagi anak—bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan yang paling kejam (PEMBERDAYAAN & ANAK, 2025). Kekerasan seksual terhadap anak, terutama oleh orang terdekat seperti orang tua atau paman, merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan diatur dalam berbagai dasar hukum, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76D, 76E, 81), UU TPKS No. 12 Tahun 2022, Konvensi Hak Anak Pasal 19 dan 34, serta UU KDRT No. 23 Tahun 2004, yang semuanya menegaskan larangan, perlindungan, serta pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terutama bila dilakukan dalam lingkungan rumah tangga. Berdasarkan data KPAI, pada tahun 2023 tercatat 262 kasus kekerasan seksual terhadap anak, di mana mayoritas pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban (Noviansah, 2024). KPAI juga mencatat 265 laporan mengenai kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2024 (Firdausya, 2025). Realitas ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan lagi sekadar isu pribadi, melainkan situasi darurat dalam perlindungan anak yang memerlukan tindakan serius dan sistematis dari berbagai sektor. Sebagaimana dinyatakan oleh Komisioner KPAI, Ai Maryati Solihah (Pirnando, 2024), “Kalau dilihat dari tren, penyebabnya beragam ya. Tetapi, yang paling banyak tercatat di KPAI itu penyalahgunaan relasi kuasa,” Pernyataan ini memperlihatkan betapa persoalan ini melampaui batas hukum dan memasuki ranah pelanggaran hak asasi anak yang paling mendasar, yaitu hak perlindungan anak sesuai dengan pasal 34 Konvensi Hak Anak (CRC) Diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang perlindungan anak dari bentuk eksploitasi seks dan penyalahguaan seksual. Kekerasan dalam lingkaran keluarga ini tidak hanya menyebabkan trauma berlapis bagi korban, tetapi juga menggambarkan lemahnya literasi pengasuhan berbasis hak anak di tengah masyarakat. Kasus Garut menunjukkan bahwa sistem pengawasan sosial di tingkat komunitas tidak berjalan efektif, dan pengasuhan alternatif yang seharusnya memberi perlindungan justru membuka celah baru bagi kekerasan. Karena itu, isu ini mendesak untuk dibahas secara mendalam agar publik dan negara tidak lagi menormalisasi kekerasan dalam ruang privat dengan dalih sebagai urusan rumah tangga.
Kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh orang terdekat yang terjadi di Kabupaten Garut pada April 2025 mengungkap lapisan kelam dalam sistem pengasuhan dan perlindungan anak di Indonesia. Seorang anak perempuan berusia lima tahun menjadi korban kekerasan seksual berulang yang dilakukan oleh ayah dan pamannya sendiri, tepat setelah diasuh oleh kakek pasca perceraian orang tua dan kematian nenek. Fakta ini menggambarkan bagaimana lingkungan domestik yang semestinya aman justru menjadi ruang kekerasan, akibat lemahnya pengawasan, ketidakhadiran orang tua, dan kurangnya edukasi pengasuhan dalam keluarga besar. Temuan darah di pakaian korban oleh tetangga menjadi titik awal pengungkapan kasus, dengan hasil visum yang menunjukkan robekan pada selaput dara, menandakan telah terjadi persetubuhan berulang. Kasus ini mempertegas urgensi perlindungan berbasis hak anak yang selama ini belum terimplementasi secara menyeluruh dalam sistem sosial masyarakat.
Secara struktural, kasus ini menunjukkan ketidakberhasilan sistem perlindungan anak dalam mencegah serta menanggapi kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Pelaku dapat dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76D jo Pasal 81 atau 76E jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara, tetapi tindakan hukum bukan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pengasuhan, hak anak, dan prosedur pelaporan kekerasan masih sangat minim. Lembaga seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan tempat perlindungan belum berfungsi secara optimal, serta pengawasan berbasis komunitas tidak dilaksanakan dengan baik. Diperlukan intervensi dari berbagai sektor untuk memperkuat sistem pendeteksian dini, pemulihan psikososial bagi korban, serta pendidikan untuk masyarakat dan pengajar terkait perlindungan anak. Kasus ini menjadi pengingat bahwa tanpa upaya yang terkoordinasi dan sistematis, rumah dapat menjadi lingkungan paling berbahaya bagi anak-anak, dan tindakan kriminal seperti ini akan terus terjadi dengan diam. Kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh orang terdekat, seperti yang terjadi di Kabupaten Garut tahun 2025, menunjukkan secara nyata krisis pengasuhan dalam konteks keluarga Indonesia, yang tidak hanya gagal melindungi anak, tetapi juga menjadi sumber utama kekerasan. Dalam proses penanganan kasus, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan pentingnya menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Setiap langkah harus mengedepankan perlindungan atas hak privasi, keselamatan, serta pemulihan psikososial anak korban. Oleh karena itu, identitas korban dirahasiakan demi menjaga hak anak atas kerahasiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Tindak Kekerasan Oleh Ayah Kandung Di Banjarnegara, KPAI Dorong Proses Hukum Berkeadilan Dan Perlindungan Korban, 2025).
Berdasarkan teori Ecological Systems Theory dari Bronfenbrenner, lingkungan mikro seperti keluarga memiliki peran fundamental dalam pembentukan perlindungan dan perkembangan anak (Crawford, 2020). Ketika sistem mikro (keluarga) rusak, maka anak berada dalam kondisi sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Dalam kasus ini, absennya peran orang tua yang kompeten, lemahnya kontrol sosial komunitas (meso system), serta tidak efektifnya dukungan dari lembaga perlindungan anak (exo dan macro system) berkontribusi besar terhadap kegagalan sistemik dalam melindungi korban. Temuan penelitian dari Save the Children (2022) juga menegaskan bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak di Asia Tenggara dilakukan oleh orang terdekat, dan seringkali tidak terungkap karena faktor relasi kuasa dan budaya diam di lingkungan domestik.
Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus serupa di Yogyakarta tahun 2021, di mana anak perempuan berusia 7 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh paman kandung. Ketika diselidiki, ternyata keluarga korban mengalami disfungsi pasca-cerai dan pengasuhan dilakukan tanpa pendampingan negara. Kasus ini tidak terungkap selama hampir satu tahun karena lingkungan sosial tidak memiliki mekanisme pelaporan yang aman, dan keluarga takut akan stigma. Hanya setelah anak mengalami gangguan emosional berat dan tidak mau sekolah, barulah kasus tersebut teridentifikasi oleh guru kelas yang kemudian menghubungi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Ini menguatkan pandangan bahwa pola asuh berbasis hak anak harus mencakup pelibatan aktif komunitas sekolah, tokoh masyarakat, serta dukungan sistemik dari lembaga layanan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusional dan yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 72A, 72B, dan 72C yang mengatakan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang wajib dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa. Secara praktis, pendekatan berbasis trauma-informed care perlu diintegrasikan dalam semua lini intervensi, dari sekolah hingga rumah aman, untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan yang utuh. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya hadir dalam bentuk hukuman terhadap pelaku, tetapi harus secara aktif memperbaiki sistem pengasuhan dan menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang benar-benar aman dan berdaya bagi anak-anak.
Untuk menjawab tantangan ini, masyarakat perlu dilibatkan sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan sosial yang peduli dan tanggap terhadap perlindungan anak. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membentuk kader perlindungan anak di tingkat RT atau RW yang dibekali dengan pengimplementasian program pelatihan pola asuh yang menghormati hak anak bagi keluarga, termasuk keluarga besar yang menjadi wali anak, serta membangun sistem deteksi dini terhadap risiko kekerasan. Selain itu, perlu dibangun budaya tidak menyalahkan korban melalui kampanye publik dan pelibatan tokoh masyarakat dalam menyuarakan pentingnya menghentikan kekerasan seksual terhadap anak. Komunitas juga dapat menginisiasi forum warga ramah anak sebagai ruang diskusi reguler tentang isu pengasuhan, penguatan keluarga, dan perlindungan anak.
Lembaga pendidikan, khususnya guru PAUD dan sekolah dasar, memiliki peran strategis sebagai pendengar pertama dan pengamat perubahan perilaku anak. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Menggarisbawahi bahwa partisipasi aktif sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang melindungi, menghargai, dan memenuhi hak-hak anak. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pelatihan psikososial dan pendidikan seksual komprehensif yang disesuaikan dengan tahap usia anak. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan anak mengenali tubuhnya, tetapi juga memberikan keterampilan untuk berkata “tidak” pada sentuhan yang tidak nyaman dan tahu cara melapor dengan aman. Selain itu, sekolah juga dapat menyediakan mekanisme pelaporan yang aman seperti “kotak aman” agar anak bisa menyampaikan keluhannya secara tertulis tanpa rasa takut.
Sosialisasi dan literasi perlindungan anak harus dilakukan secara masif melalui kampanye berkelanjutan di berbagai institusi seperti sekolah, posyandu, dan komunitas lokal guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan prosedur pelaporan kekerasan.
Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membangun kebijakan yang berpihak pada anak melalui regulasi yang konkret dan alokasi anggaran yang responsif terhadap isu kekerasan. Peraturan daerah yang mewajibkan setiap desa memiliki sistem perlindungan anak berbasis komunitas merupakan langkah awal yang penting. Selain itu, dibutuhkan sistem informasi anak berisiko yang mampu mengidentifikasi anak-anak dari keluarga yang mengalami perceraian, kemiskinan ekstrem, atau pengabaian. Selain itu, pengembangan layanan pengasuhan alternatif yang responsif, dimana pemerintah daerah harus menyediakan skema asuhan alternatif yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berkelanjutan agar anak-anak yang kehilangan pengasuhan orang tua tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak.Pemerintah juga perlu menyediakan rumah aman ramah anak yang dilengkapi dengan tim rehabilitasi psikososial, termasuk psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum.
Terakhir, sektor hukum dan lembaga layanan perlindungan anak harus menjamin proses hukum yang berpihak pada korban, dengan memastikan bahwa anak tidak dipertemukan langsung dengan pelaku selama proses persidangan. Layanan bantuan hukum gratis dan pendampingan psikologis sangat penting untuk keluarga miskin yang sering kali tidak tahu ke mana harus melapor atau takut menghadapi proses hukum yang berbelit. Keseluruhan pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya intervensi multi-level dan lintas sektor yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan.
Bottom of Form
Penegakan hukum yang tegas dan transparan perlu diterapkan melalui proses yang cepat dan adil, serta mempublikasikan kasus tanpa mencantumkan identitas korban. Ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Diharapkan, pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersahabat bagi anak-anak serta menurunkan angka kekerasan seksual dalam keluarga dan masyarakat. Dengan membangun ekosistem perlindungan anak yang komprehensif—yang melibatkan masyarakat, pendidik, pemerintah, dan lembaga hukum—Indonesia dapat menciptakan tempat yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memastikan adanya sistem pencegahan dan pemulihan yang adil dan berdasarkan hak anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar tanggung jawab individu. Hal ini harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan, budaya, dan praktik sehari-hari.
Sumber Referensi:
Crawford, M. (2020). Ecological Systems Theory: Exploring the Development of the Theoretical Framework as Conceived by Bronfenbrenner. Journal of Public Health Issues and Practices, 4(2), 2–7. https://doi.org/10.33790/jphip1100170
Firdausya, I. (2025). KPAI Terima 2.057 Aduan Sepanjang 2024, Kasus Terkait Balita Paling Banyak. Metro TV. https://www.metrotvnews.com/read/NleC8M5q-kpai-terima-2-057-aduan-sepanjang-2024-kasus-terkait-balita-paling-banyak
Noviansah, W. (2024). KPAI: 262 Kasus Kekerasan Anak di 2023, 153 Kasus Libatkan Ibu Kandung. Detik News. https://news.detik.com/berita/d-7376053/kpai-262-kasus-kekerasan-anak-di-2023-153-kasus-libatkan-ibu-kandung?
PEMBERDAYAAN, K., & ANAK, P. D. P. (2025). Kliping Digital KPAI Periode 1-14 April 2025. Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun, II(1), 17–18.
Pirnando, T. (2024). KPAI Sebut Relasi Kuasa Jadi Penyebab Kekerasan Seksual Anak. Sin Po.Id. https://sinpo.id/detail/73166/kpai-sebut-relasi-kuasa-jadi-penyebab-kekerasan-seksual-anak?
Tindak Kekerasan Oleh Ayah Kandung di Banjarnegara, KPAI dorong proses hukum Berkeadilan dan Perlindungan Korban. (2025). Humas KPAI. https://www.kpai.go.id/publikasi/tindak-kekerasan-oleh-ayah-kandung-di-banjarnegara-kpai-dorong-proses-hukum-berkeadilan-dan-perlindungan-korban